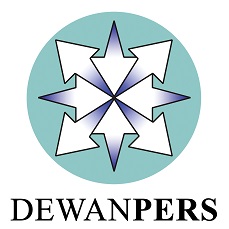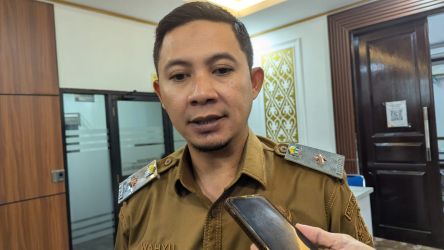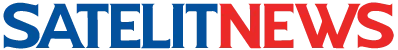Menguji Ide Rousseau Dalam Praktik Pilkada di Indonesia

JEAN Jacques Rousseau, lewat karya populernya The Social Contract (Du contract social; ou, Principes du droit politique, 1762) membangun argumen bahwa kedaulatan tidak dapat diwakilkan. Baginya, kehendak umum (volonte generale) hanya realistis bila setiap warga negara terlibat langsung. Boleh dikata, Rousseau lebih suka pilkada langsung ketimbang dipilih DPRD. Kira-kira begitu.
Bila dicermati, gagasan Rousseau pada dasarnya mengandung kelemahan fundamental pada tiga aspek utama. Pertama, potensial tirani mayoritas. Konsep kehendak umum yang ia imajinasikan kehilangan relevansi. Faktanya, apa yang diasumsikan sebagai kepentingan bersama hanyalah suara mayoritas yang membungkam hak minoritas.
Atas dasar one man one vote itu, suara minoritas terdidik (dosen, guru, pemikir, birokrat, aktivis dll) yang kurang lebih 37 persen di Indonesia tak memiliki arti. Cukong yang membiayai paslon lebih tertarik berinvestasi pada 63 persen konstituen tak cukup terdidik dan miskin (tak sekolah, SD, SMP, dan SMA). Merekalah mayoritas berpengaruh. Suara Penjual Siomay sama dan sebangun dengan suara seorang guru besar.
Kedua, imposibilitas skala. Dalam konteks itu, Rousseau hanya membayangkan demokrasi langsung pada kontestasi seluas Negara Kota seperti Polis, Jenewa atau Singapura. Ketika Athena pasca penaklukan menjadi negara bangsa yang luas, ide Rousseau tampak utopis secara logistik. Mekanisme langsung mustahil menyediakan waktu yang efisien dan efektif melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Sebagai negara bangsa terbesar keempat di dunia, apa yang dipikirkan Rousseau menemukan relevansi dari kesulitan dan kemahalan logistik. Alokasi Rp 71 triliun Pilkada 2024 di luar ongkos setiap paslon plus pilkada susulan tak signifikan melahirkan pemimpin berkualitas. Ada baiknya angka sebanyak itu dialokasikan pada program nasional seperti MBG, Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih. Andai Rousseau bangkit kembali, ia tentu akan segera melakukan revisi.
Ketiga, pengabaian pluralisme. Rousseau cenderung menolak eksistensi kelompok-kelompok kepentingan. Padahal dalam masyarakat modern, keberagaman kepentingan adalah keniscayaan. Menuntut satu suara bulat justru memicu otoritarianisme atas nama rakyat.
Apa yang terjadi selama ini semua mengatasnamakan rakyat. Padahal, rakyat miskin dieksploitasi tak hanya oleh oligarki, cukong, pemodal, timses, juga lembaga pengatur angka elektabilitas (surveyor) yang memanfaatkan algoritma untuk memandu persepsi bagi kepentingan paslon. Di situ kapitalisasi suara bersembunyi senyap lewat quick count, real count, dan exit poll.
Implikasi semua itu, pertama, demokrasi lokal di Indonesia cenderung menjadi ritus lima tahunan semata. Publik menjalani prosedur demokrasi namun kehilangan esensi kehendak umum karena pemilih dimanipulasi oleh politik uang dan populisme-demagog. Kehendak rakyat bukan lahir oleh diskursus rasional, tapi mobilisasi emosional.
Kedua, ide Rousseau tentang kesatuan kehendak faktanya hanya fatamorgana. Pilkada nyatanya mencipta dikotomi “kita dan mereka.” Alih-alih melahirkan konsensus nasional, faktanya gesekan atas nama politik identitas mengikis soliditas berbangsa dan bernegara. Sekeluarga bisa bertengkar-dendam untuk pilihan paslon yang berbeda bertahun-tahun.
Ketiga, meski rakyat memilih langsung, faktanya proses pencalonan dikuasai oligarki. Ini hanya ilusi kedaulatan, di mana rakyat merasa punya kuasa memilih paslon, padahal menu yang ada telah disaring oleh elit. Ini adalah paradoks di mana ide Rousseau digunakan untuk melegitimasi sistem yang justru bersifat aristokratis-oligarkis.
Tak berbeda dengan pilkada tak langsung, keduanya punya cacat bawaan, di mana parpol turut menyaring sekaligus memilihnya atas usulan dari atas dan mendengar input dari bawah. Kita tinggal memilih mekanisme mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan masalah kita. Kebutuhan kita bagaimana berkuasa semudah dan semurah mungkin. Masalah kita bagaimana korupsi dan money politics yang melandai ke lapisan pori-pori kulit paling bawah dapat diminimalisasi.
Kritik terhadap gagasan Rousseau di Indonesia menunjukkan bahwa pilkada secara langsung saja tak cukup. Tanpa literasi politik, penegakan hukum terhadap money politics, dan perlindungan minoritas, mekanisme pilkada secara langsung hanya menjadi alat bagi tirani mayoritas yang dibungkus oleh retorika kedaulatan rakyat.
Indonesia seyogyanya membutuhkan keseimbangan, di mana partisipasi langsung tetap diperlukan untuk memilih wakil terbaiknya. Selanjutnya para wakil memilih pemimpin sebagaimana amanah sila keempat Pancasila. Dengan begitu kita dapat memastikan ide kehendak umum Rousseau bukan sekedar angka di kertas suara, melainkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.(*)
Penulis merupakan Ketua Harian Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) dan Guru Besar pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Olahraga | 2 hari yang lalu
Olahraga | 1 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Pos Tangerang | 1 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu