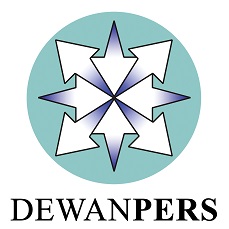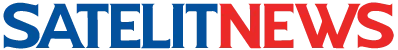Hak Kaya dan Etika Publik

SETIAP kita umumnya memilih kaya dibanding miskin. Imaji kaya dideskripsikan sebagai seseorang yang memiliki harta banyak dalam bentuk properti, investasi maupun sumber daya bernilai. Kaya diasosiasikan pula kemampuan seseorang melakukan segala hal tanpa batas karena dukungan finansial. Kekayaan berhubungan dengan status sosial, kekuasaan, dan prestise dalam struktur sosial.
Sebaliknya, kaya melawan realitas miskin. Miskin digambarkan minus sumber daya ekonomi. Kaum papa adalah mereka yang tuna akses pada kebutuhan dasar. Ragam kemiskinan paling ekstrem dipengaruhi aspek struktural dan kultural. Hal pertama berada di pundak pemerintah, sisanya merupakan mentalitas masyarakat yang membutuhkan intervensi kolektif.
Perspektif kaya dan miskin memiliki banyak muka. Dalam wajah religi, kaya dan miskin bergantung pada kesholehan penganutnya. Kaya misalnya, diakui bila seseorang mampu mempertanggungjawabkan cara memperoleh dan menggunakan harta buat kebajikan. Maknanya bisa meluas ke aspek non materi seperti kekayaan hati dan pikiran untuk berbagi.
Hal yang sama soal status miskin. Label miskin kerap disematkan pada mereka yang kaya sekalipun. Demikian sebaliknya. Mereka dapat dikategorikan miskin jiwa atau miskin rohani. Artinya, mereka yang miskin harta bukan berarti miskin jiwa. Kaum spiritualis sering dikunjungi kaum hartawan hanya untuk meminta wejangan atau sesuatu yang bersifat mistik. Relasi itu memperjelas relativitas kaya dan miskin dalam pengetahuan yang saling memberi.
Menjadi kaya seperti eks pejabat pajak dan bea cukai tentulah keinginan manusia pada umumnya. Dengan kaya kita dapat berbagi dengan kaum miskin. Dalam rational choice kita menggunakan berbagai cara guna memperoleh hasil dengan sesedikit mungkin pengorbanan. Begitu kira-kira ilmu ekonomi-politiknya. Menjadi kaya pun memberi kita tempat terbaik dalam strata sosial. Kita bisa diterima di kompleks rumah mewah, kumpulan Rubicon atau motor gede (moge).
Andai para petugas pajak terlihat sedang membagi-bagi harta buat kaum miskin dan rumah ibadah, mungkin publik tak peduli asbab kekayaan sebanyak itu. Masalahnya ketika publik dihimpit kewajiban pajak yang terus melangit, mereka justru disuguhi kemewahan hidup para "debt collector" pajak. Pemicunya arogansi anak si kaya pada orang lain. Di situ bukan saja perilaku yang terkoreksi, kekayaan pun dipersoalkan dari sisi etika publik, religi dan hukum.
Etika publik mengadu soal ketidakadilan rasa, benar dan patutkah? Ketidakadilan sistem hukum diragukan bekerja pasca insiden pemukulan anak petinggi Ansor. Asumsinya, dengan kekayaan, hukum dapat dikontrol. Teknologi mempercepat barang bukti disaksikan publik, sekaligus bertindak sebagai yuri sebelum pengadilan sejatinya digelar. Gugatan itu merembes ke mana-mana, melabrak muka 13.000 pegawai Kemenkeu yang disinyalir alpa melapor pajak (CNBC, 2023).
Moralitas religi tak sekejam moralitas publik. Religi hanya menyoal dari mana kekayaan dan ke mana dibelanjakan. Itupun berlaku nanti di akhirat. Karena kita ada di dunia, maka hukum dunialah yang digunakan untuk membuktikan dari mana seseorang mengantongi kekayaan sebanyak Rp 56 miliar. Sejauh dapat dibuktikan tentu bukan soal. Mungkin saja itu warisan orang tua, bukan warisan para bandit pengemplang pajak.
Sekali lagi, kita berhak kaya sebagai manusia normal. Dengan kaya kita bisa membayar pajak sebanyak mungkin. Namun begitu, kekayaan sepatutnya diperoleh secara sehat dan wajar. Sehat dalam arti berasal dari sumber yang jelas dan digunakan sesuai kebutuhan. Wajar dalam makna sesuai dengan pekerjaan kita. Tentu beda seseorang yang bekerja dengan risiko besar dibanding seseorang yang hanya menunggu hantaran tuyul tiap malam Jumat Kliwon.
Menghentikan cara kaya dengan melompat pagar rupa-rupanya tak bisa hanya dengan mengubah sistem tunjangan yang jomplang antara pengumpul pajak dengan seorang lurah yang tugasnya membujuk masyarakat agar bayar pajak. Lagi-lagi kita butuh tindakan etik pimpinan organisasi seraya menunggu proses hukum yang lamban. Beruntungnya teknologi kini membantu kita menggelar perkara lebih awal di dunia maya sebelum hakim membongkarnya di pengadilan.(*)
*) Penulis adalah analis pada Pusat Kajian Strategis Pemerintahan Jakarta
Pos Tangerang | 2 hari yang lalu
SEA Games 2025 | 2 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
SEA Games 2025 | 2 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
SEA Games 2025 | 10 jam yang lalu
SEA Games 2025 | 1 hari yang lalu
Pendidikan | 2 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu