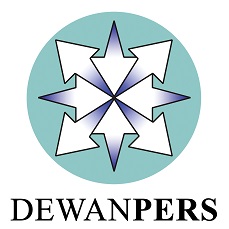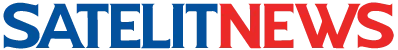Sastra Dan Psikologi Manusia Indonesia

SERPONG - Selama beberapa bulan terakhir emosi bangsa ini terkuras oleh tayangan persidangan Ferdi Sambo, istrinya berikut kroni-kroninya, atas peristiwa penembakan terhadap Brigadir Yosua. Secara linguistik, Yosua (Joshua) berasal dari bahasa Ibrani yang berarti perlindungan dari Tuhan. Nama Yosua merujuk pada seorang rasul yang diutus Tuhan setelah kerasulan Nabi Musa yang memimpin bangsa Israel. Persidangan terbuka di meja hijau, hendaknya dapat membuka mata-hati masyarakat Indonesia akan pentingnya era keterbukaan dan kejujuran. Sehingga, terbukanya aib dan kesalahan atas kezaliman manusia terhadap manusia lain, dapat menjadi hikmah bagi bangsa ini agar senantiasa bermuhasabah, introspeksi, dan bercermin diri.
Situasi ini tak mungkin kita hindari. Akibat dari kemajuan transformasi yang saling bersinambung antara satu dengan yang lainnya. Boleh jadi akan dianggap gangguan atau batu sandungan bagi pihak-pihak tertentu yang merasa keberatan, sebagaimana amarah dari tokoh utama dalam novel terbaru Hafis Azhari, “Jenderal Tua dan Kucing Belang” (selanjutnya ditulis JTKB). Penulis novel tersebut, bersama generasi milenial yang tak mau terlibat untuk menikmati “nasi tumpeng” yang disodorkan Orde Baru, seakan mampu berdiri tegak, melampaui tinjauan filosofis perihal hakikat kepribadian manusia Indonesia (pasca kekuasaan militerisme).
Kucing belang sebagai salah satu tokoh penting, tiba-tiba muncul di pekarangan rumah mewah itu, seakan memahami dari mana tanah dan rumah yang dihuni keluarga besar jenderal tua itu. Secara religius, dengan fasih novel itu mengungkap akibat dari harta-harta haram yang “dimakankan” kepada anak-cucu kesayangan sang jenderal. Tak ubahnya dengan bangkai-bangkai yang menggerogoti hati dan jiwa anak-anak keturunan, baik hati dalam pengertian organik maupun metafisik.
Saya merasakan adanya kelimbungan dalam narasi sebagian sastrawan kita akhir-akhir ini. Mereka tergopoh-gopoh memasuki kualitas wacana tentang ulasan karya sastra, baik di media luring maupun daring. Ada saja seniman yang berujar dalam perbincangan Ngopi Bareng, bahwa penyebab utamanya adalah pesatnya teknologi informasi. Loncatan budaya Indonesia dari masyarakat agraris, bahkan belum juga tegak menjadi masyarakat literer melalui tradisi membaca cetakan (koran, majalah maupun buku) tiba-tiba dihantam badai prahara, memasuki era revolusi digital yang seakan mendesak dan memaksakan kehendak.
Bahkan, kita pun ditantang untuk membaca perasaan dan pikiran kita sendiri, yang membuat banyak pihak kebakaran jenggot seakan belum siap menghadapi kenyataan terungkapnya hakikat dan identitas keindonesiaan. Terlebih jika sastra itu bicara fasih mengenai aib dan kesalahan kita sendiri, sebagaimana tokoh-tokoh dalam novel Perasaan Orang Banten.
Penulis novel tersebut yang dilahirkan sebagai etnis Jawa Banten, satu tanah kelahiran dengan wakil presiden K.H. Ma’ruf Amin (bukan Kuat Ma’ruf), seakan ingin menguji kesiapan bangsa ini pada kedewasaan berpikir. Menilik dari karakteristik penulisnya, novel JTKB justru lebih kalem dan tenang ketimbang Perasaan Orang Banten (2012). Meski keduanya jauh dari tuduhan sebagai sastra pendendam dan pendengki, yang kerap disematkan oleh angkatan milenial kepada sastrawan dan seniman yang mewarisi harta karun Orde Baru (baca NU Online: Lomba Membuat Kue Serabi).
Terlepas dari banyaknya buku tentang teknik dan tips-tips menulis, atau bahkan berbagai training tentang penulisan sastra dan artikel di zaman Orde Baru, saya perlu menegaskan bahwa memang ada rumus-rumus yang hanya dikuasai oleh penulis yang baik, orang-orang tertentu yang karyanya akan terus dibaca dan dikenang sepanjang masa. Jadi, bukan perkara produktif atau tidak. Juga bukan soal puluhan atau ratusan buku yang telah digarap seorang penulis. Karena pembaca yang baik dan jenius, senantiasa akan terkoneksi pikirannya dengan kualitas (software) bacaan yang baik pula.
Boleh saja mengacu dari karya-karya eksistensialisme Barat, khususnya Eropa, tetapi karakter khas alienasi bangsa kita tetap berbeda dengan orang-orang Eropa maupun Amerika. Begitupun konsep mitologi Jawa yang memandang hidup sebagai persinggahan sementara, yang juga berbeda dengan pandangan mitologi Hindu di India tentang konsep maya maupun mukswa.
Jadi, untuk membaca manusia Indonesia masakini, seorang penulis harus tergenangi iklim religiositas maupun filsafat Indonesia juga. Misalnya, bagaimana harus mendalami unsur irasionalitas yang ada pada masyarakat kita, yakni dunia bawah sadar yang tak mampu mereka bahasakan. Bahkan, sifat-sifat yang tak sanggup mereka kendalikan, meski pada dasarnya mereka ingin menjauhi hal-hal yang bersifat naluriah hewani itu.
Pada prinsipnya, kemunculan novel JTKB bukan digagas dari urusan emosi satu-dua orang, atau like or dislike. Apalagi urusan itu hanya meributkan honor atau royalti mengenai berhak atau tidaaknya suatu karya mesti diterbitkan. Kalau begitu, naïf dan dangkal sekali urusan kesusastraan Indonesia selama ini. Terkait dengan itu, penulis JTKB tak mau berurusan dengen kepentingan-kepentingan yang bersifat semu dan sesaat. Ia memandang fenomena kepribadian manusia sebagai keseluruhan dirinya, juga keseluruhan semesta raya, seakan bernaung dalam kemaslahatan.
Manusia merupakan lahan atau tanah-tanah tak bertuan (terra incognita) yang mesti digarap dan ditelusuri secara manusiawi dan ilahiah (makro). Memang fokusnya pada persoalan kekinian atau problema manusia Indonesia pasca-1965, tetapi penulisnya sanggup menangkap sinyal, menuangkan narasi agung yang melampaui batasan-batasan ruang dan waktu. Ia menelusuri kedalaman relung jiwa dan psikologi manusia Indonesia, setelah bertahun-tahun menjelajahi alam bawah sadar mereka, melalui riset dan penelitian bertajuk historical memory Indonesia bersama sejarawan Asvi Warman Adam, Hermawan Sulistyo, Goenawan Mohamad, hingga mantan tapol Hersri Setiawan dan Joesoef Isak.
JTKB memang berbeda dari karya-karya Pramoedya. Meskipun penulisnya pernah berguru pada Pramoedya, tetapi ia mampu menciptakan kreasi pasca-Pram. Bukan bersikap dendam atau pemberang pada kolonialisme, tapi ia lebih cenderung pada persoalan-persoalan psikologis, sebagai akibat dari dampak yang ditimbulkan iklim kolonialisme. Ia mampu meyoal kedalaman makna, bagaikan tafsir manusia laboratorium yang bereksperimen dengan mesin diesel yang paling mutakhir.
Meskipun kita menyadari bahwa kompleksitas hidup tentu lebih rumit daripada sekadar menampilkan sosok figur maupun tokoh. Tetapi paling tidak, pergelutan pemikiran selama puluhan tahun yang diteladani penulis dan sastrawan, merupakan teladan mulia dari pencarian konsep tentang filsafat dan religiositas manusia Indonesia secara otentik.
Bagaimanapun, karya sastra JTKB seakan memberikan teladan agar para penulis – khususnya angkatan muda – tidak berkarya secara serampangan dan mubasir, yang akan mudah terhempas oleh perjalanan ruang dan waktu. Kita harus senantiasa menjelajahi alam bawah sadar kolektif, tentang impian-impian hingga mitos-mitos baru manusia Indonesia, yang tak bisa dihindari bahwa kita pun telah menjadi bagian dari manusia hiper modern juga.(*)
Pos Tangerang | 2 hari yang lalu
SEA Games 2025 | 1 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
SEA Games 2025 | 2 hari yang lalu
Pos Banten | 23 jam yang lalu
Pos Banten | 1 hari yang lalu
Pos Tangerang | 1 hari yang lalu
Pos Banten | 1 hari yang lalu
Pos Tangerang | 1 hari yang lalu