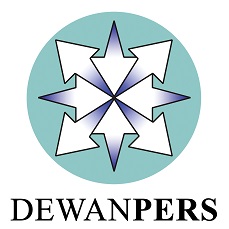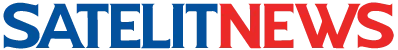Hati Kota Hati Kita

SERPONG - Kota bukan hanya soal jalan, drainase, dan bangunan. Kota juga punya hati. Ia bisa teduh, bisa murung, bisa marah, bahkan bisa trauma. Dan seperti manusia, hati kota bergantung pada bagaimana ia diperlakukan. Apakah dipelihara dengan rasa, atau dibiarkan tergerus oleh ambisi.
Tangerang Selatan hari ini tumbuh cepat. Tapi pertanyaannya, tumbuh ke arah mana? Apakah hati kotanya ikut dibangun, atau hanya lapisan permukaannya saja? Warga merasakan jalan yang makin mulus, tapi juga kesenjangan yang makin terasa. Taman makin banyak, tapi interaksi sosial makin renggang. Kota jadi sibuk, tapi bukan berarti sehat.
Dalam tasawuf, hati (qalb) adalah pusat kehidupan batin. Imam al-Ghazali menyebut hati sebagai raja dalam tubuh manusia—yang menentukan arah hidup, bukan sekadar pengikut. Maka, jika kota kita ingin benar-benar hidup, yang harus dibangun pertama bukan hanya gedung, tapi juga qalb al-madīnah—hati kota.
Sayangnya, banyak kebijakan hari ini hanya menimbang data, bukan rasa. APBD dirancang dengan kalkulasi, tapi minim empati. Proyek infrastruktur dijalankan tanpa cukup mendengar warga yang terdampak. Orang-orang kecil—pedagang kaki lima, ibu-ibu kampung, pengemudi ojek, pengajar ngaji—sering kali hanya jadi catatan kaki. Padahal merekalah denyut sebenarnya dari hati kota.
Dalam Adab al-Muluk, al-Mawardi menulis bahwa pemimpin sejati adalah “yang hatinya bergetar ketika mendengar rintihan rakyat.” Tapi di mana ruang bagi getar hati dalam tata kelola kota modern? Apakah kita masih punya forum yang mendengar bukan hanya suara keras, tapi juga suara lirih dari gang-gang sempit?
Ibn ‘Arabi mengajarkan bahwa alam semesta adalah bayangan dari al-Qalb al-Kullī—hati semesta. Kota pun demikian. Ia adalah pantulan dari kondisi batin kolektif warganya. Jika pemimpinnya kering kasih, maka jalan akan keras. Jika masyarakatnya saling menyimpan curiga, maka drainase pun tak mengalir lancar. Maka membangun kota tak bisa dilepaskan dari membangun jiwa.
Filsuf kontemporer dari Maroko, Taha Abdurrahman, menyebut pentingnya tathqīf al-ḥass—pengasahan kepekaan sebagai dasar kebijakan publik. Pemerintahan yang kehilangan sensitivitas akan kehilangan arah. Maka, dalam konteks Tangsel, kita perlu bertanya: sudahkah hati kota ini tersambung dengan hati warganya?
Beberapa langkah bisa mulai ditempuh. Pertama, memperkuat musrenbang berbasis narasi, bukan hanya angka. Libatkan tokoh lokal, guru ngaji, anak muda, dan komunitas adat dalam menyusun rencana pembangunan. Kedua, wujudkan Ruang Dengar Kota—forum informal di tiap kecamatan untuk menyerap rasa dan cerita warga, bukan sekadar aduan teknis. Ketiga, tanamkan budaya adab dalam pelayanan publik: mendahulukan senyum dan salam sebelum form dan syarat.
Tangerang Selatan bukan Jakarta. Tapi ia punya potensi menjadi kota yang hidup dari dalam. Kota yang warganya merasa dihargai bukan hanya saat pemilu. Kota yang memberi ruang untuk bernafas, bercengkerama, bersujud, dan berharap.
Seperti hati manusia, kota pun bisa terluka. Ia bisa retak oleh pembangunan yang gegabah, atau mengering oleh birokrasi yang dingin. Tapi ia juga bisa disembuhkan. Dengan empati, partisipasi, dan cinta yang nyata. Karena pada akhirnya, kota ini adalah cermin. Jika hati kotanya sehat, warganya akan kuat. Tapi jika hati kota retak, kita semua akan merasa asing di rumah sendiri.
Mari kita rawat hati kota ini, sebagaimana kita ingin hati kita sendiri dirawat. Dengan mendengar, dengan mencinta, dan dengan mendoakan. Sebab Tangsel bukan hanya tempat tinggal. Ia adalah tempat tumbuh. Dan tempat tumbuh harus dijaga hatinya—oleh semua, untuk semua.
Nasional | 2 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
TangselCity | 1 jam yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu