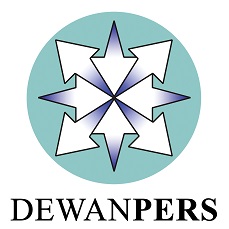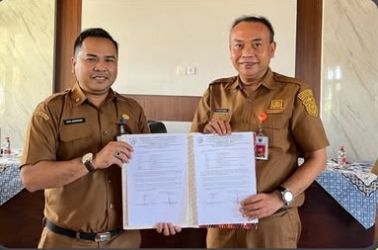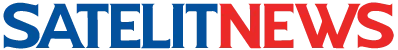Transendensi di Jantung Kota

SERPONG - Kita sering menyangka bahwa spiritualitas adalah milik tempat-tempat sunyi: masjid di puncak gunung, saung di pinggir sawah, atau surau kecil yang jauh dari keramaian. Tapi bagaimana jika transendensi justru bisa—dan harus—hadir di tengah kota? Di antara deru kendaraan, pusat belanja, dan kawasan komersial, adakah ruang tersisa untuk menyapa Tuhan?
Tangerang Selatan kini tumbuh menjadi kota strategis yang ramai siang malam. Tapi pertanyaan paling hakiki bukan seberapa banyak mal dan flyover yang dibangun, melainkan seberapa dekat warganya dengan keheningan batin. Transendensi—kemampuan manusia untuk mengangkat jiwanya ke arah yang lebih tinggi—adalah kebutuhan warga urban yang semakin mendesak.
Dalam Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, Imam al-Ghazali menyebut bahwa hati manusia seperti cermin: jika terlalu banyak debu duniawi menempel, ia kehilangan kemampuan memantulkan cahaya Ilahi. Maka, yang kita butuhkan bukan hanya kota yang bersih secara fisik, tapi juga ruang hidup yang memungkinkan cahaya itu kembali menyinari batin. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi manusia produktif tapi kehilangan arah.
Faktanya, banyak ruang publik di Tangsel belum ramah bagi spiritualitas. Data dari Dinas Cipta Karya (2024) menyebutkan bahwa hanya 34% pusat komersial besar di Tangsel yang menyediakan tempat ibadah layak. Musala publik sering tersembunyi di pojok parkiran atau sempit dan pengap. Padahal, tempat sujud yang nyaman bukan sekadar fasilitas, tapi ekspresi keberadaban kota.
Transendensi bukan urusan agama saja. Ia juga menyentuh soal desain, etika pembangunan, dan arah kebijakan. Dalam tasawuf, sebagaimana dijelaskan Syekh Abdul Qadir al-Jilani, “Tidak ada jarak antara dunia dan akhirat, kecuali lapisan kesadaran.” Artinya, kota bisa menjadi medan ibadah jika disusun dengan kesadaran. Jalanan, taman, bahkan halte, bisa menjadi tempat dzikir—jika ruang itu memberi tempat bagi jiwa, bukan hanya bagi kendaraan.
William C. Chittick menegaskan bahwa dunia modern telah terlalu menyempitkan pengalaman spiritual hanya pada ritual, padahal hakikat transendensi ada pada “kesadaran hadir”—conscious presence—di setiap aktivitas. Maka, pertanyaannya bukan apakah kita punya waktu untuk beribadah, tapi apakah ruang kota kita memberi peluang untuk menghidupi makna itu.
Seyyed Hossein Nasr, pemikir filsafat Islam kontemporer, mengingatkan bahwa modernitas telah memutus hubungan antara manusia dan pusat spiritualitasnya. Kota dibangun di atas logika efisiensi, bukan kebijaksanaan. Ruang publik didesain untuk lalu lintas barang dan uang, bukan lalu lintas batin. Maka Tangsel, jika ingin tumbuh sebagai kota modern-beradab, harus berani menyisipkan aspek transendensi dalam perencanaan ruang.
Beberapa langkah bisa dimulai: pertama, menjadikan keberadaan rumah ibadah sebagai indikator dasar dalam perizinan ruang publik. Bukan sekadar formalitas, tapi indikator kualitas spiritual. Kedua, mendesain ruang refleksi di kantor-kantor pelayanan publik, agar birokrasi tak kehilangan ruh kemanusiaannya. Ketiga, mendorong kebijakan urban spiritual literacy—pengenalan nilai-nilai tafakkur, dzikir, dan adab dalam lingkungan kerja dan pendidikan.
Pemerintah Kota Tangsel juga bisa melibatkan komunitas tarekat, pesantren urban, serta majelis taklim progresif dalam forum-forum pembangunan. Bukan hanya untuk ritual, tapi untuk menghadirkan narasi kebijaksanaan dan batin dalam proses teknokratik yang sering terlalu kaku. Jangan sampai kota hanya dibangun oleh logika beton, tanpa disentuh oleh logika batin.
Rumi menulis: “Carilah Tuhan, bukan hanya di atas sajadah. Temuilah Dia di tengah pasar, saat kau memberi harga dengan kejujuran, dan membungkus barang dengan kasih.” Maka transendensi di kota bukan ilusi. Ia adalah keniscayaan—jika kita mau menatanya.
Karena sejatinya, kota ini tidak hanya dihuni oleh kendaraan dan angka statistik, tapi oleh manusia yang membawa luka, harapan, dan kerinduan akan makna. Jika Tangsel ingin tumbuh sehat, ia harus menjadi ruang di mana warga bisa sujud di tengah pasar, berdzikir di tengah deadline, dan mengenal Tuhan bahkan saat antre di ruang tunggu. Inilah wajah kota yang utuh: jantungnya tetap berdetak, tapi nadinya mengalirkan dzikir.
Nasional | 1 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu